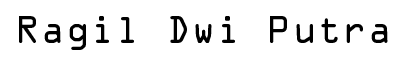Apa yang Tak Terlihat dari “yang Lain”
dalam Karya “Meraut Dalam yang Lain”
oleh : Gatari Surya Kusuma
“Ternyata memang diri kita sendiri adalah organisasi yang juga perlu diatur”. Itulah perkataan Ragil yang terngiang dalam pikiran saya ketika selesai berbincang dengan Ragil dan mulai untuk menentukan arah tulisan saya.
Karya yang berjudul “Meraut Dalam yang Lain” adalah karya fotografi staging atau karya fotografi yang memanggungkan
subyek foto dengan kesadaran berkarya. Subyek utama dalam foto adalah dirinya sendiri yang mengenakan pakaian milik orang lain. Ia mengajak kurang lebih seratus orang untuk berpartisipasi meminjamkan baju agar Ragil kenakan lalu ia bercermin dan berfoto. Foto yang diambil adalah proyeksi diri Ragil ke cermin.
Ragil membagikan pengalamannya ketika ia berkeinginan untuk mengumpulkan 183 foto dalam waktu 11 bulan yang harus berubah menjadi 153 foto. Tentu saja perubahan angka ini telah melalui pertimbangan yang tidak sebentar. Ia harus bergulat dengan egonya yang ingin menghasilkan sebuah karya terbaik. Jadi, proses menentukan 153 foto ini salah satu hal penting untuk dicatat dan dipelajari lebih dalam guna mengetahui bagaimana Ragil bekerja dalam penciptaan karya seninya. Ini adalah salah satu proses pengaturan diri yang disebut dalam kutipan Ragil, “ternyata memang diri kita adalah organisasi yang juga perlu diatur”.
Dari sini kami sepakat akan melihat tubuh Ragil tidak hanya ada Ragil, melainkan membongkarnya satu per satu. Mulai dari ego, representasi, hingga bahasa visual yang muncul dari performativitasnya sebagai Ragil secara sadar maupun tidak sadar–selanjutnya akan menjadi petunjuk untuk menemukan makna “yang Lain” dalam karya berjudul “Meraut Dalam yang Lain”.
Masa Transisi
Ragil memulai karir keseniannya dari pengalamannya sebagai mahasiswa di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 2010 jurusan Seni Rupa, Grafis Murni. Ia banyak menguji coba medium kekaryaannya. Mulai dari cetak saring, video hingga performance. Hingga ia tergabung ke dalam sebuah organisasi yang memiliki fokus untuk mengulik media dan film yaitu Forum Lenteng di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Keterlibatannya dalam Forum Lenteng menajamkan kepekaannya terhadap medium video dan performance. Mengingat, aktivitasnya di Forum Lenteng selain terlibat aktif dalam sesi pengorganisasian festival film, ia juga aktif dalam kelompok belajar performance bernama 69 Performance Club. Dalam kelompok belajar itu, mereka bersama-sama mengulik tentang apa itu performance hingga mencoba untuk mereproduksi pengetahuan atas tubuh dan mewujudkannya ke dalam sebuah kesadaran performance.
Setelah dua tahun berkecimpung dalam aktivitas kerja dan belajar kolektif, ia memutuskan untuk meneruskan karirnya sebagai Ragil seorang diri tidak lagi sebagai 69 Performance Club maupun Forum Lenteng. Kegamangan jelas terjadi setelahnya. Kebiasaan yang terbentuk selama dua tahun harus ia rombak habis-habisan. Apalagi, dua tahun bukan waktu yang sebentar untuk menciptakan sebuah kebiasaan yang berhubungan dengan kerja kesenian dan rutinitas harian.
Jika sebelumnya ia harus mempertimbangkan posisinya sebagai bagian dari kelompok sekaligus bekerja sebagai representasi sebuah kelompok, kali ini ia harus berdiri sendiri sebagai Ragil. Jika sebelumnya ia tidak perlu memikirkan bagaimana ia menciptakan aktivitas rutin harian, kali ini ia harus menciptakannya sendiri karena tidak lagi ada jadwal rutin pertemuan kelompok setiap harinya. Jika sebelumnya ia tidak perlu memikirkan biaya pemasukan dasar untuk makan dengan porsi sederhana, kali ini ia harus memikirkan penggantinya karena ia tidak lagi mendapatkannya dari Forum Lenteng.
Dari sinilah Ragil mengalami masa transisi dalam karir berkesenian dan kehidupan sehari-harinya yang juga penting sebagai proses pendewasaannya dalam berkesenian. Dalam tulisan ini saya akan mencatat masa transisi sebagai lokus dari idenya untuk menelurkan karya “Meraut Dalam yang Lain” sekaligus proses penemuan makna atas “yang Lain” dalam proses kesenian Ragil sebagai seniman.
Melihat “yang Lain”
Melalui Pembagian Elemen Fotografi
Ragil menggunakan kata “yang Lain” untuk menceritakan bahwa ia bersama orang di luar dirinya dalam pembuatan karya ini. Ia meminjam baju-baju yang menjadi identitas khas orang lain. Lalu untuk menjadikannya bagian dari proyek ini, ia memotret dirinya di depan cermin sembari mengenakan baju-baju yang telah ia pinjam. Ia terus melakukan itu hingga terkumpul sebanyak 153 foto. Lalu, ia sajikan dalam sebuah galeri dengan cara menggabungkannya menjadi video. Saya sempat hadir di pamerannya pada saat itu. Saya tidak begitu bisa melihat pakaian yang ia kenakan. Saya hanya menyaksikan bahwa Ragil mengenakan banyak pakaian yang berbeda. Saya juga menangkap ada beberapa detik melihat Ragil tampak tidak seperti yang saya kenal dengan pakaian yang terlihat sempit.
Namun, saya akan coba untuk mengesampingkan cara penyajian video tersebut. Tulisan ini akan membahas karya Ragil dalam penyajian buku foto ini. Tentu saja, saya bisa menikmatinya dengan sangat perlahan dan khidmat. Saya saksikan satu persatu, dan menyaksikan raut wajah Ragil yang berubah kesan mengikuti pakaian yang ia kenakan. Kadang ia tampak manis, lembut, tampan, lugu, begundal, bahkan konyol. Semua citra itu terbentuk dari pakaian yang Ragil kenakan–karena ia menggunakan latar belakang, sudut pengambilan, dan ekspresi yang serupa.
Jika Roland Barthes dalam bukunya berjudul Camera Lucida menyatakan bahwa dalam melihat sebuah karya fotografi, penting untuk memulainya dari studium dilanjutkan dengan punctum. Studium adalah memaknai simbol-simbol yang ada dalam gambar sebagai sumber informasi yang membawa satu bentuk komunikasi[1]. Jadi melihat foto baju sebagai representasi dari baju yang dimiliki oleh seseorang atau terkait dengan identitas pribadi atau kelas sosial hingga pekerjaan tertentu yang melekat di baju tersebut. Pada tataran ini, bisa disebut sebagai proses eksplorasi obyek di dalam foto. Saya masih bisa menikmati foto Ragil satu per satu sembari melihat detail baju-baju yang dikenakan oleh Ragil membawa identitas tertentu atau tidak.
Lalu, punctum akan bekerja untuk mengembalikan seluruh simbol kepada keterikatannya dengan si penonton. Atau bisa dibilang dengan memberikan celah kepada penonton untuk menangkap simbol dan menjadikan obyek sebagai tanda atau kode atas sesuatu. Barthes menyebutnya sebagai elemen kedua fotografi yang mengganggu keberadaan studium[2]. Dalam proses ini, obyek sudah bukan menjadi titik perhatian. Obyek telah melebur ke dalam simbol tanpa harus mengikuti simbol sosial karena yang bekerja dengan keras adalah simbol fotografis. Kumpulan foto Ragil tidak lagi dimaknai satu per satu, melainkan dimaknai sebagai sebuah kumpulan foto untuk menunjukan “yang Lain”.
Lalu setelah punctum, S.T Sunardi menyebutnya sebagai waktu ketiga atau satori. Satori adalah masa reflektif. Tahap ini saya diharuskan untuk melepaskan diri dari fotografi atau kumpulan karya foto Ragil. Saya tidak lagi terpatok kepada formalis fotografi yang dihadirkan oleh studium dan punctum, melainkan saya telah pergi meninggalkannya jauh untuk bisa mencari kisah dan makna saya sendiri setelah melihat karya ini. Saya lakukan ini untuk memaknai “yang Lain”.
Ketiga proses ini harus dilakukan secara berurutan agar bisa sampai pada pemaknaan “yang Lain”. Situasi lainnya, jika tidak memahaminya dari obyek, akan sulit sebagai pembaca bisa menemukan makna “yang Lain” dari berlembar-lembar foto serupa. Lebih tepatnya agar tidak tersesat di dalam limpahan foto yang serupa. Atau bahkan terjebak dalam imajinasi atas identitas yang dibawa oleh pakaian-pakaian yang dikenakan oleh Ragil[3].
Paling tidak momen satori setelah melalui studium dan punctum menyadarkan saya bahwa ada nilai lainnya di luar identitas yang dibawa oleh pakaian. Misalnya dengan kecurigaan “apa yang sedang ingin Ragil sampaikan dengan menghadirkan ratusan foto serupa dengan pakaian berbeda? Lalu menggunakan terma “yang Lain” sebagai inti dari pesan. Ada sebuah rentetan panjang atas pemaknaan “yang Lain” yang perlu saya gali lebih dalam melalui tulisan ini.
Dalam tahap satori ini, saya mengembalikan kepada perasaan berlebihan yang saya dapat ketika melihat ratusan foto ini. Saya terus bertanya-tanya bagaimana bisa 153 foto ini ada dan apa yang membuatnya berhenti di angka 153 foto–karena sebelumnya Ragil menyebutkan bahwa rencana awal adalah mencapai 183 foto? Pertanyaan inilah yang menggiring saya untuk bisa mencari hubungan antara makna ego dalam berkarya, representasi yang hadir melalui foto, dengan bahasa yang hadir tanpa perlu dan mampu didefinisikan melalui aksi performance yang ia hadirkan dalam bentuk fotografi.
Masa Satori
Seperti yang sudah saya jabarkan di atas, bahwa karya ini hadir sebagai penanda dari satu rutinitas lama menuju satu rutinitas yang baru. Ini perlu ditandai sebagai satu perjalanan estetik Ragil sebagai seorang seniman. Dunia seniman berkolektif dan dunia seniman mandiri memang sangat berbeda. Meskipun medannya sama yaitu kesenian. Namun, ada aktivitas dan metode pengkaryaan yang sama sekali tidak bisa disamakan. Selanjutnya akan mengantarkan si seniman menghadapi tantangan dunia kesenian yang juga sangat berbeda.
Seorang individu dalam bahasa inggris bisa dimaknai dengan kata “person”. Yang mana “person” berasal dari bahasa Yunani yang berarti topeng, selanjutnya bisa diperpanjang menjadi “citizen” atau individu yang memiliki hak atas kota atau legal person[4]. Saat ini “person” dimaknai sebagai satu keunikan manusia yang bersifat tunggal. Sehingga setiap individu memiliki preferensi dan nilai “unik”nya masing-masing. Penjelasan tentang makna kata “person” atau yang merujuk kepada kata individu–dalam konteks tulisan ini–menegaskan bahwa satu entitas makhluk hidup yang memiliki hak dan kedaulatannya sendiri.
Jika merujuk pada makna kata kolektif, maka artinya adalah sekumpulan dari individu-individu dengan aktivitas dan berada di dimensi ruang, waktu yang sama. Sedangkan setiap individu memiliki nilai keunikan dan kedaulatannya masing-masing. Bisa dibayangkan dan dipastikan bahwa hubungan yang terbangun antara individu dan kolektif harus bersifat dinamis. Tidak bisa memiliki satu hubungan yang statis dalam jangka waktu lama. Situasi ini yang membuat tantangan menjadi seniman berkolektif dan seniman mandiri menjadi berbeda. Jika seniman mandiri, tidak perlu disibukkan untuk memikirkan dan menjaga hubungan dinamis antara kolektif dan individu. Jika tidak dijaga dan hubungannya menjadi statis, maka bisa jadi ada ketidak seimbangan antara kolektif dan individu. Misalnya salah satunya telah berhasil mendominasi satu yang lain, sehingga menciptakan hubungan yang statis–tidak dinamis. Sedangkan seniman mandiri juga harus bekerja mengorganisir keseluruhan kerjanya oleh dirinya sendiri.
Masa transisi yang dialami Ragil menjadi berarti dan penting dicatat karena bisa dibilang Ragil sedang berpindah dunia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang berubah dalam masa transisi ini? Saya mencatat ada perihal ego dan ambisi, representasi Ragil sebagai individu dan kolektif, dan akhirnya mampu menghasilkan bahasa atas pengalaman yang telah dikodefikasi menjadi sebuah karya.
Dalam perbincangan awal dengan Ragil, saya menggaris bawahi perubahan rencana dari menciptakan 183 foto menjadi hanya 153 foto. Ini bukan tanda buruk, namun ini menggiring saya untuk bisa mengumpulkan kepingan makna “yang Lain”. Ragil menggunakan cermin sebagai cara untuk menunjukkan bahwa proyeksi cermin yang ditangkap oleh kamera Handphone itu adalah “yang Lain” meskipun menggunakan tubuh ragil. Cermin dipilih karena sifatnya yang bisa memantulkan sebuah obyek. Pantulannya tidak bisa disebut sebagai bukan obyek atau bukan realita, melainkan itu tetap obyek dan tetaplah realita. Namun diperlukan “mata” yang lain untuk bisa menangkap realita apa di sana.–khususnya dalam karya ini.
Ragil bermain-main dengan persepsi pantulan cermin ini. Aktivitas mengaca memang sudah menjadi kebiasaan untuk Ragil. Namun bercermin dengan tidak menggunakan pakaian yang biasa ia kenakan, ditambah lagi dengan intensitas yang lebih dari biasanya membuatnya terus berhadapan dan mempertanyakan dirinya–terutama dirinya yang ada di dalam cermin. Alih-alih mengambil gambar dirinya yang sedang bercermin, Ragil lebih memilih untuk menampilkan dirinya yang ada di dalam cermin. Imaji ini semakin menguatkan bahwa yang ingin Ragil tonjolkan adalah individunya “yang Lain”. Jadi, proses penciptaan karya ini pun menggiring Ragil untuk memaknai realita dirinya yang tampak di dalam cermin.
Menciptakan Rutinitas
Sekaligus Proses Pendewasaan dalam Berkarya
Ragil memperlakukan kolaborator yang meminjamkan pakaian seperti hubungan patron dan klien. Ia menjelaskan ide karyanya kepada mereka, lalu menjelaskan cara kerja peminjaman seperti waktu dan cara pengirimannya. Jika setuju, maka Ragil akan mendapatkan pakaiannya. Pemilihannya pun Ragil tidak memiliki kategorisasi yang pasti. Ia mulai dari orang terdekat, orang yang dianggap “berpengaruh”, hingga teman-teman yang berbeda kota sekiranya ia bisa melakukan negosiasi ini.
Ragil menjaga pakaiannya dengan sangat baik. Ia berusaha untuk mengembalikan pakaian sesuai durasi waktu yang telah disepakati. Layaknya seorang patron yang tidak menginginkan kliennya kecewa. Untuk mengantisipasi itu, Ragil benar-benar mendedikasikan waktu dan energinya untuk ini. Jadi bisa dihitung bahwa kerja penciptaan karyanya bukan hanya proses memotretnya saja, melainkan seluruh proses dari menghubungi hingga proses berkomunikasi setelahnya. Bahkan, penciptaan buku ini adalah salah satu janji yang Ragil sampaikan kepada kolaborator. Bisa dibilang, ia harus menunaikan ini sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang seniman yang menginisiasi hubungan kolaborasi.
Semua pekerjaan itu Ragil kerjakan seorang diri. Lantas, ia menemukan pembanding antara ketika ia berkolektif dan sendiri. Sebelumnya, ia tidak pernah mengerjakan keseluruhan pekerjaan ini seorang diri. Karena tentu saja, beban pekerjaan akan dibagi dengan sesama anggota kolektif. Situasi ini yang akhirnya menggiring Ragil bahwa ia menemukan batas atas dirinya. Ia tidak perlu terhimpit untuk terus melakukan–meskipun dengan kesadaran performance–demi mencapai satu ambisi. Ia menyadari ketika ia mencapai angka 153 dan merasa bahwa ia tidak sanggup lagi melanjutkan. Selain karena terhimpit waktu berpameran, juga karena keterbatasan pikiran, energi, waktu, dan uang. Paling tidak di titik ini Ragil berhasil untuk mencapai kebenaran atas dirinya yang berdaulat–yaitu berhasil untuk jujur kepada dirinya bahwa ia harus menghargai batas diri.
Kegelisahan dan situasi yang mendesak Ragil agar berhenti di angka 153 adalah kenyataan lain yang–barangkali–tidak ia sadari ketika ia berada dalam kolektif. Ia harus menjalankan organisasi mandiri yaitu dirinya sendiri. Sampai tulisan ini diketik yaitu Maret 2020, Ragil masih menjalani pola pola pengorganisasian yang terbawa dari pengerjaan karya ini. Ia masih selalu melihat ketepatan waktu adalah yang penting, hubungan yang terbangun dengan kolaborator bukanlah untuk sementara atau berbasis kepentingan, keterbukaan dalam bernegosiasi penting untuk dilakukan terus. Apalagi ketika ia berurusan dengan seratus lebih orang, tentu saja ada pola berkomunikasi dalam dirinya yang ia sadari dan berubah menjadi kebiasaan.
Penutup
Kebiasaan-kebiasaan itu barangkali tidak terlihat secara gamblang di dalam karya Ragil atau proyeksi yang terpapar di cermin ketika Ragil bercermin mengenakan pakaian orang lain. Kebiasaan dan keresahan itu bisa terlihat ketika Ragil telah menjadikan semua aktivitas itu menjadi kebiasaan. Sebuah kesadaran dan aktivitas yang telah menubuh memang lahir dari rutinitas. Namun, kesadaran yang ia temukan berkaitan dengan masa transisinya dari berkolektif hingga menjadi seniman mandiri adalah satu pengalaman estetika yang patut untuk dicatat sebagai proses pendewasaan diri khususnya dalam berkesenian. Karena sebuah kesadaran yang humanis memang tidak lahir begitu saja.
Mengingat bahwa kesadaran yang humanis adalah bersifat sangat personal, maka perlu ada proses yang terus membenturkan manusia hingga menemui kesadarannya. Seperti satori yang datang di akhir dan memberi jarak untuk mengendapkan sekaligus merenungkan tentang apa yang telah ada–atau terlihat. Barangkali memang tugas Ragil selanjutnya setelah karya ini adalah memikirkan bagaimana membagi atas hal-hal “yang Lain” kepada penonton yang tidak mengalami pengalaman serupa dengan Ragil yang terus “bercermin” hingga menemukan dirinya “yang Lain”.
***
[1] Lihat essay S.T Sunardi yang berjudul “Waktu Ketiga”.
[2] Roland Barthes. 1981. Camera Lucida. London: Vintage, hal 27.
[3] Pernyataan ini tidak bermaksud untuk mengerdilkan makna identitas yang melekat dengan baju dan siapa yang memakai. Namun, khususnya dalam karya “Meraut dalam yang Lain”, makna dari identitas pakaian yang dikenakan lagi rupanya bukan inti makna “yang Lain”. Selanjutnya akan saya jabarkan di tulisan di bawah.
[4] Casa Tres Patios. 2014. Praxis and Context: Art, Pedagogy and Community. Colombia: Especial Impresore. Hal:27
Daftar Pustaka
Barthes, Roland. 2000. Camera Lucida. New York: Vintage Publishing
Lazarin, Saza, dkk. 2016. Praxis and Context: Art, Pedagogy and Community. Columbia: Especial Impresores S.A.S
Sunardi, S.T. 2012. Vodka dan Birahi Seorang “Nabi”. Yogyakarta: Jalasutra
Suryajaya, Martin. 2016. Sejarah Estetika. Yogyakarta: Indie Book Corner
Tentang Penulis :
Gatari Surya Kusuma lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Kini tinggal di Yogyakarta untuk belajar Fotografi di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Ia juga punya ketertarikan dengan perspektif etnografis dalam melakukan kerja-kerja fotografi.